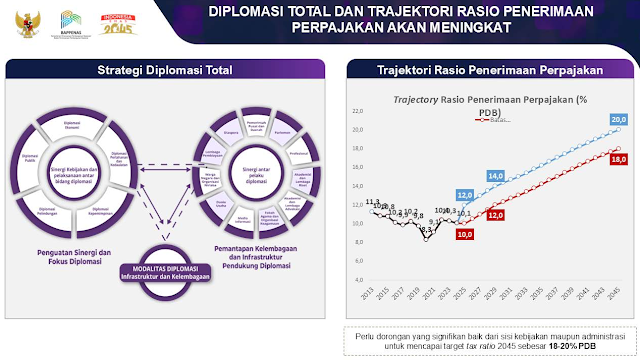Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Penduduk miskin adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. BPS menggunakan garis kemiskinan (GK) untuk menetapkan penduduk miskin. GK mencerminkan minimum biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan yang setara dengan 2.100 kkal dan non makanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dll. Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari GK.
Adalah Erik Thorbecke, Joel Greer dan James Foster memperkenalkan indeks kemiskinan pada tahun 1984 dengan persamaan:
Kalau kita perhatikan formula FGT pada Gambar 1, nilai indeks P0, P1, dan P2 akan bernilai kurang dari 1. Tapi mengapa P0 bisa lebih dari 1. Jawabnya mudah, karena P0 dikali 100 sehingga P0 bisa bernilai lebih dari 1. Pendek kata, mengubah proporsi menjadi persentase perkara yang tidak sulit bukan? Bagaimana dengan nilai indeks P1 yang juga lebih dari 1? Artikel inilah jawabannya.
Kalau indeks kemiskinan FGT dihitung apa adanya, nilai ketiga indeks akan menghasilkan nilai sebagai berikut :
0 <= P2 <= P1 <= P0
Pada saat y (rata-rata pengeluaran per kapita per bulan) bernilai nol maka
P0 = P1 = P2
Sebaliknya, jika y sama dengan z (garis kemiskinan) maka
P0 = P1 = P2 = 0
Di sisi lain, saat nilai y < z maka besaran indeks bergantung pada nilai alpha (0, 1, dan 2). hubungan ketiga indeks kemiskinan FGT akan berlaku
P2 < P1 < P0
Dengan demikian, nilai indeks kemiskinan pada saat dirilis bukan nilai alamiahnya tetapi merupakan hasil pengalian dengan konstanta 100 sehingga nilai P0, P1 dan P2 bisa lebih dari 1. Itulah sebabnya, P0 dinyatakan dalam persen. Bagaimana dengan P1 dan P2? Karena P1 dan P2 diberlakukan sama dengan cara dikalikan dengan nilai 100 semestinya, P1 dan P2 juga kita baca dalam satuan persen. Jika kita merasa janggal dengan satuan persen untuk indeks kedalaman kemiskinan, yang menyatakan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, bisa menggunakan alternatif lain yaitu basis poin. Tetapi 1 basis poin sama artinya dengan satu per 10.000. Artinya 1 persen = 100 basis poin.
Jika satuan basis poin digunakan, maka nilai indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 1.55 persen akan dibaca 155 basis poin. Dibandingkan dengan September 2018, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2019 turun sebesar 8 basis poin.
Memahami Garis Kemiskinan (GK)
Berikut adalah penjelasan beliau terkait pertanyaan, “Mengapa membandingkan kemiskinan antar daerah tidak menggunakan garis kemiskinan yang sama?”
Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2.100 kkalori per kapita per hari)
Garis kemiskinan non makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya.
Penghitungan GK di Indonesia mempunyai sejarah panjang.
Saat krisis terjadi tahun 1998, BPS bersama pakar dari Universitas sepakat untuk menyempurnakan penghitungan angka kemiskinan supaya dapat membandingkan kemiskinan antara daerah dan antar waktu dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi daerah. Dibuatlah GK absolut yang terdiri dari GK Makanan dan Non Makanan.
Pada awalnya, tahun 1998, GK dihitung dengan menggunakan metode PPP (metodenya seperti penghitungan daya beli di komponen hidup layak di IPM atau PPP yang digunakan di World Bank. Dipilih sejumlah basket komoditi, dipilih daerah acuan). Dengan menggunakan metode tersebut, GK yang dihitung di setiap provinsi menjadi lebih representatif karena sudah memperhatikan karakterisktik setiap daerah, dan terbanding antar waktu dan daerah (terbanding disini bukan dalam pengertian harus menggunakan GK yang sama).
GK tahun 1998 ini digunakan dalam penghitungan tahun berikutnya (disebut GK sementara yang kemudian diinflate dengan Inflasi),dan dijadikan dasar penghitungan GK tahun 1999. Proses yang sama dilakukan setiap tahun sd dengan sekarang (lihat publikasi Metode Kemiskinan BPS).
Sekedar perbandingan, kalau kita menggunakan GK yang sama diseluruh provinsi di Indonesia hasilnya justru tidak mencerminkan kondisi di daerah. Contoh yang nyata adalah metode kemiskinan World Bank/WB. WB menggunakan GK yang sama di seluruh negara yaitu 1,25 US$ PPP dan 2 US$ PPP. Yang sering dijadikan kritikan adalah dengan menggunakan 2 US$ di Amerika yang lumayan kaya, besaran GK tsb tidak berarti apa2, terlalu rendah dan bisa2 tidak ada orang miskin. Sebaliknya dengan menggunakan 2 US$ PPP di Bangladesh yang masih miskin, GK tersebut menjadi terlalu besar.
Menakar Anggaran Pengentasan Kemiskinan
Penduduk miskin adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. BPS menggunakan garis kemiskinan (GK) untuk menetapkan penduduk miskin. GK mencerminkan minimum biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan yang setara dengan 2.100 kkal dan non makanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dll. Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari GK.
Singkat kata, jumlah kebutuhan minimum anggaran untuk pengentasan kemiskinan adalah perkalian antara indeks kedalaman kemiskinan, jumlah penduduk dan garis kemiskinan. Kita akan mengaplikasikan formula penghitungan jumlah kebutuhan minimum anggaran untuk pengentasan kemiskinan pada Data Kemiskinan di Provinsi Papua Barat pada September 2013. Kebutuhan anggaran minimal untuk pengentasan kemiskinan khususnya pada Cluster 1 yaitu kelompok penduduk miskin yang membutuhkan “ikan” di Provinsi Papua Barat dirinci menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 1. Mungkin saja, pemerintah Kabupaten/Kota telah menganggarkan biaya pengentasan kemiskinan lebih dari yang dibutuhkan. Jika demikian, yang perlu dilakukan adalah realokasi anggaran pengentasan kemiskinan yang ada pada pos-pos yang lebih tepat. Pengendalian harga kebutuhan pangan khususnya bahan makanan pokok menjadi salah satu kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. Hampir 80 persen GK ditentukan oleh Garis Kemiskinan Makanan. Hanya 20 % GK disumbang oleh Garis Kemiskinan Non Makanan.

https://statistikaterapan.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/03/menakar-kebutuhan-anggaran-pengentasan-kemiskinan-revisi.pdf
Dikutip dari :
https://statistikaterapan.wordpress.com/2020/01/18/menelisik-indikator-kemiskinan-bps/
https://statistikaterapan.wordpress.com/2016/01/21/memahami-garis-kemiskinan/